
KEDAULATAN RAKYAT DAN PANCASILA
Oleh: Santiamer Silalahi

Abstraksi
“……..dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab………”
UUD NRI Tahun 1945 merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat. Sikap futuristik Johannes Latuharhary yang menolak Indonesia Timur bergabung dengan Indonesia merdeka jika frasa “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya,” tetap dicantumkan dalam konstitusi senantiasa tetap relevan, karena tidak sesuai dengan Sila-3 dan-4 Pancasila.
Kata Kunci : Kedaulatan Rakyat, Pancasila.
Abstract
“……..in a Constitution of the State of Indonesia, which is formed in a structure of the Republic of Indonesia with people’s sovereignty based on the Almighty God, Just and Civilized Humanity …………………….”
The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is a manifestation of people’s sovereignty. Johannes Latuharhary’s futuristic attitude that rejects Eastern Indonesia joining independent Indonesia if the phrase “with the obligation to implement Islamic law for its adherents” is still included in the constitution, it will always remain relevant, because it is not in accordance with Principles 3 and 4 of Pancasila.
Keywords: People’s Sovereignty, Pancasila.
A. Pendahuluan
Sejak awal para bapak pendiri bangsa telah sepakat, bahwa Indonesia merdeka adalah negara demokrasi, hal ini dapat dibuktikan dengan kalimat : “……… UUD Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat….” Sebagaimana tercantum dalam alinea-4 pembukaan UUD NRI tahun 1945.1) Pada intinya, demokrasi adalah sistem pemerintahan dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat Dalam negara demokrasi, rakyat berhak memilih pemimpin dan wakil-wakilnya, terlibat dalam pembuatan keputusan politik serta memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan dan mengawasi jalannya pemerintahan. Demokrasi dan kedaulatan rakyat adalah dua konsep yang keterkaitannya erat. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang dirancang untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan dan keadilan, sedangkan kedaulatan rakyat adalah fundamentum sistem demokrasi.
Baca Juga: Mengurai Jalan Keadilan Agraria, Orasi Ilmiah Prof. Dr. Aarce Tehupeiory di UKI
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Sekretariat Jendral MPR RI, 2015. Hlm.115.
Pasal 1 ayat 2 UUD NRI tahun 1945 sebelum perubahan berbunyi, “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Artinya, MPR merupakan lembaga tertinggi negara yang memegang kekuasaan superior.2) Sesudah perubahan, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ada perubahan mendasar soal pelaksana kedaulatan rakyat sebelum dan sesudah perubahan, yaitu dari sepenuhnya oleh satu lembaga tertinggi negara bernama MPR menjadi menurut UUD.
Lembaga negara di Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu constitutional state organ
dan state auxiliary organ. Constitutional state organ merupakan lembaga negara yang
pembentukannya mendapatkan kewenangan langsung dari Undang-Undang Dasar, sementara state auxiliary organ merupakan lembaga negara yang kewenangannya berasal dari peraturan perundang-undangan.3)
Pasca amandemen UUD 1945, setidaknya ada 34 lembaga negara yang kewenangannya diamanatkan langsung oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Selain itu, hingga tahun 2017 terdapat 104 lembaga negara independen yang ada di Indonesia yang keberadaannya diatur oleh peraturan perundang-undangan.4)
2) UU Nurul Huda, Hukum Lembaga Negara (Bandung: Refika Aditama, 2020), 56
3) Kelik Iswandi dan Nanik Prasetyoningsih, “Kedudukan State Auxiliary Organs dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia,” Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan 1, no. 2 (2020): 138–39.
Lembaga negara independen dapat diartikan sebagai sebuah lembaga yang terbentuk dari pemerintah yang menyerahkan kewenangan-nya untuk menetapkan atau membentuk badan sendiri (the agencies produced by the growing trend of government power to appointed or self appointed bodies). Jadi, lembaga negara independen ini dapat diartikan sebagai kehendak negara untuk membuat lembaga baru yang anggotanya diambil dari unsur non negara, dan diberi otoritas negara dan dibiayai oleh negara tanpa harus menjadi pegawai negara.5)
Amandemen konstitusi UUD 1945 tahun 1999 sampai 2002 merupakan perubahan besar ketatanegaraan di Indonesia. Hal tersebut memicu lahirnya banyak lembaga negara independen atau pun komisi-komisi negara. Sekitar tahun 1914 ketika krisis ekonomi melanda dunia, Amerika Serikat yang menjadi kiblat negara-negara demokrasi menghendaki adanya lembaga baru yang khusus mengatur dunia bisnis. Tujuannya adalah untuk mengawasi persaingan dunia bisnis, sehingga munculah lembaga Federal Trade Comission. Pada periode selanjutnya, muncullah lembaga-lembaga baru atau disebut komisi negara independen seperti The Consumer Product Safety Commission, Federal Communication Commission, Interstate Commerce Commiss-ion.
4) Laurensius Arliman, “Kedudukan Lembaga Negara Indonesia Untuk Mencapai Negara Hukum,” Jurnal Kertha Semaya 8, no. 7 (2020): 1039.
5) Bunyamin dan Huda, “Politik Hukum Pelembagaan Komisi-Komisi Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” 94.
Baca juga: Dr John Palinggi: Polri di Usia 79, Dekat dengan Masyarakat, Modern, dan Penuh Integritas
Adapun tujuan pembentukan lembaga negara bantu oleh negara adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Dengan adanya lembaga yang lebih fokus pada tugas tertentu, diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih baik dan lebih cepat. Selain daripada itu, juga untuk menangani bidang-bidang tertentu yang membutuhkan keahlian khusus, seperti perlindungan konsumen, pemberantasan korupsi, pengawasan peradilan, pengawasan pelaksanaan hak asasi manusia, dll.
Dengan adanya perubahan pelaksana kedaulatan rakyat dan banyaknya lembaga negara baik main state dan auxiliary state organ memunculkan tiga pertanyaan krusial yang memerlukan jawaban disertai jalan keluar. Pertama, apakah perubahan dan penambahan lembaga negara utama dan lembaga negara bantu akan semakin mempermudah rakyat melakukan pengawasan terhadap pemerintahan negara atau justru sebaliknya? Kedua, mekanisme apa yang akan dipakai agar setiap lembaga negara saling mengawasi sehingga tidak menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh UUD maupun oleh negara? Ketiga, persyaratan apa yang harus dipenuhi mekanisme saling mengawasi tersebut sehingga ia berfungsi efektif mewujudkan kesejahteraan dan keadilan?
B. Pembahasan
1. Sebelum Perubahan UUD NRI 1945
Negara adalah suatu organisasi manusia. Ia buatan manusia, bukan buatan Tuhan. Dalam suatu organisasi ada pembagian tugas dan mekanisme pengawasan untuk memastikan tujuan bersama tercapai.
Dalam filsafat Pancasila, negara adalah organisasi dari sekelompok manusia tertentu (sila 2 dan 3) yang berusaha untuk mencapai kehidupan bersama yang berkesejahteraan dan berkeadilan (sila 5) dengan cara musyawarah/mufakat (sila 4), namun sekelompok manusia yang berorganisasi itu menyadari, bahwa berhasil atau tidak usaha tersebut tergantung dari berkat Tuhan Yang Maha Esa (sila 1). Kesadaran tersebut mendapat tempat dalam alinea-3 pembukaan UUD 1945, bahwa mereka berhasil membentuk Indonesia merdeka hanya karena “berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa” 6)
Menurut pengajaran Barat, negara adalah suatu machts – organisasi (organisasi kekuatan) dan politik adalah machts vorming en machtsaanwending (pem-bentukan dan penggunaan kekuasaan). Setiap individu mempunyai kekuasaan dan kepentingan absolut. Jika individu-individu ini berkumpul, maka kemungkinan besar akan terjadi bentrokan di antara mereka. Oleh karena itu harus ada kekuasaan yang lebih besar untuk mengatasi bentrokan-bentrokan itu dan sekaligus menjaga agar tetap terjaga ketenteraman/keamanan dalam pergaulan hidup sehari-harinya.
6) UUD 1945, op.cit., hlm.114
Kekuasaan itu berasal dari individu-individu yang menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintahan negara yang harus menjaga ketenteramannya, tetapi tidak semua kekuasaan itu diserahkan (Locke); Selalu ada tinggal yang dinamakan hak-hak asasi.
Adapun tujuan yang merupakan cita-cita tiap individu tergantung kepada individu itu sendiri. Politik adalah cara negara untuk menjaga agar tidak terjadi bentrokan antar individu yang memiliki kekuasaan dan kepentingan yang saling berbeda dan bertentangan satu dengan lainnya. Adapun cara mencapai tujuan hidup sejahtera menurut versi masing-masing individu tergantung kepada tiap individu itu sendiri.
Pengajaran tentang negara dan politik menurut filsafat Pancasila tidak sama dengan Barat. Suku bangsa-suku bangsa serbaneka berjumlah +/- 69 juta jiwa hidup di seantero nusantara memiliki kesamaan sejarah dalam hal penderitaan karena penjajahan bangsa asing kemudian, karena didorong oleh keinginan luhur untuk berkehidupan yang merdeka, adil dan makmur, maka atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa mereka bersatu selanjtunya bermufakat untuk membentuk organisasi yang disebut negara. Tetapi amat sukar bagi +/- 69 juta jiwa ini bemusyawarah untuk mufakat maka mereka menjelmakan diri dalam suatu lembaga yang disebut Majelis Per-musyawaratan Rakyat (MPR).
Penjelmaan rakyat yang diberi nama MPR inilah yang ditugaskan oleh seluruh rakyat Indonesia untuk mewujudkan tujuan Indonesia merdeka, yaitu terlindunginya seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, sejahtera dan cerdasnya seluruh bangsa Indonesia serta turut aktif menciptakan ketertiban nasional bahkan dunia.7) Adapun jenis dan jumlah cara yang ditempuh MPR untuk mencapai tujuan negara, tidak menjadi persoalan sepanjang dipelihara budi pekerti kemanusiaan dan berpedoman pada cita-cita moral rakyat Indonesia yang luhur (bd. pembukaan UUD NRI 1945).
Menurut sistem pemerintahan Pancasila yaitu yang tercantum dalam UUD 1945, pada prinsipnya pemerintahan negara berada di satu tangan, yaitu presiden/ Mandataris. Keadaan ini menggiring kepada kesimpulan, bahwa Presiden Republik Indonesia tidak hanya sekedar kepala eksekutif seperti halnya Presiden Amerika Serikat, karena : (a) bertentangan dengan kenyataan; (b) bertentangan dengan prinsip yang mendasari organisasi Negara Indonesia yang tidak mendasarkan diri kepada kekuasaan individu, oleh karena sistem pemerintahan negara tidak mengenal adanya pembagian kekuasaan secara letterlijk : legislatif, eksekutif, dan judikatif. bukan berarti Presiden/ Mandataris diktator.
1) adanya pengawasan yang ketat dari:
– MPR
– Badan Pengawas pembantu MPR :
7) Ibid., hlm. 115
(Sambungan halaman…….4 )
a. DPR
b. DPA
a. BPK
d. Rakyat (berdasarkan kedaulatan rakyat).
– Peradilan, MA
Baca Juga: Kisah Inspiratif Profesor Aarce Tehupeiory, Dari Saparua hingga Guru Besar Hukum Agraria
2) Pemerintahannya dapat diakhiri dengan impeachment oleh MPR.8)
Dengan demikian, meskipun pemerintah-an berada pada satu tangan, tetapi bukan pemerintahan diktator. Negara-negara Barat seperti ; Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda menerapkan sistim demokrasi untuk mencegah timbulnya kekuasaan absolut di satu tangan, maka ditempuhlah pembagian kekuasaan/ wewenang negara dalam tiga cabang, eksekutif, legislatif, dan judikatif dimana kedudukan satu dengan lainnya sederajat, dan untuk menghindari kesimpangsiuran atau kekacauan diadakanlah keseimbang-an kekuasaan yang disebut checks and balances.
Dalam sistem pemerintahan Pancasila, MPR bukan hanya penjelmaan rakyat, tetapi MPR nguwongke rakyat dengan mengkanalisasi kedaulatan rakyat menjadi anggota Badan Pengawas pembantu MPR, untuk mengawasi jalannya pemerintahan tidak saja secara organisatoris melalui MPR dan DPR tetapi secara langsung melalui kontrol sosial—–
8)Kartohadiprodjo Soediman., Pantja-Sila dan/dalam Undang-Undang Dasar 1945. Binatjipta, 1968., hlm. 80-82.
(social control), artinya negara menjamin keberadaan dan kebebasan pers. Rakyat melakukan kontrol sosial terhadap implementasi segala sesuatu yang tercantum dam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), serta Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Setiap tahun.
Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) disusun dan ditetapkan oleh MPR. GBHN adalah haluan negara dalam garis-garis besar yang dibuat sebagai pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu.9)
GBHN menjadi pedoman bagi penyelenggaraan negara selama periode tertentu, biasanya lima tahun, dan menjadi acuan bagi lembaga-lembaga tinggi negara serta seluruh rakyat Indonesia dalam melaksanakan dan mengawasi pembangunan nasional di segala bidang : Ideologi, politik, ekonomi, industri, agama, sosial budaya, hukum, pertahanan dan keamanan.
Sistem pemerintahan Pancasila setidak-nya mencirikan dua kekhasan, yaitu : Pertama, MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia menyediakan dirinya bagi rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan secara organ-isatoris. Kedua, MPR meletakkan landasan implementasi prinsip cheks and balances antar sesama lembaga negara yang merupakan mandatarisnya, yaitu membuat kedudukan sesama lembaga negara sederajat (neben) satu dengan lainnya.
Baca juga: Gong Perlawanan Arus, IKA USU Jakarta dan DPD RI Bersatu Merawat Budaya Sumut di Era Modernisasi
9)Pusat Pengkajian MPR RI., Reformulasi dan Upaya Memperkokoh Sistem Perencana-an Pembangunan Nasional, 2014., hlm.2
Untuk pertama kali, MPR dibentuk berdasarkan Konstitusi RIS 1949, selanjutnya diatur dalam UUD Sementara 1950. Pada masa itu MPR berfungsi sebagai lembaga perwakilan yang memiliki kewenangan konstitusional untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Pada awal Orde Lama, terjadi penyimpangan struktur kenegeraan Indonesia dari presidensial menjadi lebih berfokus pada sistem parlementer, sehingga MPR belum memiliki peran yang menonjol. Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, penyebutan MPR menjadi MPRS mengalami transformasi signifikan menjadi lembaga tertinggi negara yang memiliki kewenangan bukan saja memilih Presiden dan Wakil Presiden tetapi memiliki kewenangan menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Sungguhpun UUD 1945 mengamanatkan bahwa anggota MPR dipilih melalui pemilihan umum, namun di awal Orde Lama, anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) diangkat langsung oleh Presiden Soekarno. Hal ini dilakukan karena adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstituante dan menetapkan MPRS sebagai lembaga tertinggi negara pada masa Demokrasi Terpimpin. Adapun anggota MPRS terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR GR) dan utusan daerah-daerah serta golongan-golongan tertentu. Presiden Soekarno menetapakan jumlah anggota MPRS 616 orang yang terdiri dari 257 orang (42 %) anggota DPR-GR, 242 orang (39 %) utusan golongan dan 118 orang (19 %) utusan daerah. Perekrutan anggota MPRS seharusnya melalui pemilihan langsung oleh rakyat, tetapi dalam praktiknya ditetapkan oleh Presiden, hal ini melegitimasi diterapkannya demokrasi terpimpin yang otoriter. Namun tuduhan otoriter tersebut dengan sendirinya terbantahkan, karena presiden menetapkan komposisi anggota MPRS mayoritas bukan berasal DPR GR (42 %) tetapi berasal dari gabungan utusan daerah dan golongan (52 %). Anggota DPR GR berasal dari partai politik dan golongan fungsional. Penetapan persentasi anggota MPRS yang demikian menunjukkan konsistensi presiden mengimplementasikan Sila-4 Pancasila. Lembaga MPRS bukan lembaga Politik, tetapi lembaga tempat seluruh rakyat Indonesia untuk bermusyawarah menyelesaikan persoalan bangsa yang tidak dapat diselesaikan secara politik semata.
Pada awal masa orde baru, diawali dengan pembersihan ideologi negara dari paparan ideologi Komunis. Presiden Soeharto memimpin negara dengan pendekatan yang otoriter dan sentralistik. Ia melakukan pembersihan menyeluruh terhadap semua lembaga negara dan pengisinya dari ideologi Komunis.
Secara ketatanegaraan, MPR tetap menjadi pusat kekuasaan pengawasan lembaga negara yang ketat. MPR adalah lembaga tertinggi negara yang memiliki kekuasaan paling tinggi di atas lembaga-lembaga negara lainnya. Ini berarti MPR memiliki otoritas tertinggi dalam sistem pemerintahan dan segala keputusan yang dibuat oleh MPR dianggap final dan mengikat.10) Hanya disayangkan pemilihan dan penetapan anggota MPR yang berasal dari utusan daerah-daerah dan golongan belum melalui mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat. Dalam struktur MPR, terdapat anggota-anggota yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan utusan daerah-daerah serta golongan yang ditunjuk oleh presiden.
Pada tahun 1971, dimulai pengubahan karakter MPR sebagai lembaga permusyawaratan menjadi lembaga politik Ketika itu Jumlah anggota MPR 920 orang, terdiri dari 460 orang (50 %) anggota DPR, 329 orang (36 %) utusan golongan dan 131 orang (14 %) utusan daerah-daerah (bd. dengan era presiden Soekarno, tidak didominasi utusan partai politik).
Di era orde baru, setidaknya terjadi tiga kali perubahan jumlah anggota MPR. Demikian juga perubahan besaran persentase anggota-anggotanya yang terdiri dari DPR, utusan daerah-daerah dan utusan golongan. Pada pemilu tahun 1977, jumlah anggota MPR sama dengan hasil pemilu 1971. Anggota dari utusan golongan turun dari 329 menjadi 325 —–
10)Azizah Rima Gitacahyani1, Farrel Arrigo., Regita Kisnanda Putri., Kuswan Hadji., Keefiktifan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Masa Orde Baru dan Masa Reformasi, Lontar Merah Vol. 7 No 1 (2024)., hlm. 807.
orang, sementara itu utusan daerah naik menjadi 235 orang dibandingkan dengan
tahun 1971. Pada tahun 1999, berjumlah 700 orang, terdiri dari DPR 500 orang, dimana 462 orang hasil pemilu dan 38 orang diangkat dari ABRI, sisanya terdiri dari utusan daerah-daerah dan golongan.
Perubahan-perubahan jumlah dan pesentase anggota MPR setiap pemilihan umum tentulah didasari peraturan perundang-undangan yang diberlakukan pada masing-masing periode.
2. Sesudah Perubahan UUD 1945
Sejak era reformasi tahun 1998, MPR Indonesia mengalami perubahan signifikan dalam kedudukan, kewenangan dan formasi keanggotaannya. Perubahan ini dilakukan dalam suasana kemarahan bathin rakyat Indonesia atas penyelenggara pemerintahan presiden Soeharto yang dinilai otoriter dan koruptif. Peranan MPR yang seharusnya mengawasi mandatarisnya telah dikooptasi untuk kepentingan kelompok dan partai sehingga prinsip check and balance tidak bekerja sebagaimana seharusnya.
Amandemen UUD 1945 yang dilakukan bertahap dari tahun 1999 hingga 2002 bukan hanya mengurangi kedudukan dan kewenangan MPR, tetapi berubah pula pelaksana kedaulatan rakyat yang sebelumnya dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, menjadi menurut Undang-Undang Dasar.11)
11) UUD 1945, op.cit., hlm. 116
Perubahan lainnya adalah penghapusan kewenangan dan peran MPR dalam menentukan arah kebijakan nasional melalui GBHN. Padahal GBHN adalah haluan negara dalam garis-garis besar yang dibuat sebagai pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu. Penilaian bahwa dengan adanya GBHN sistem pemerintahan sangat tersentralisasi sama sekali tidak tepat. Justru karena adanya GBHN seluruh penyelenggara pemerintahan mulai dari pusat sampai ke daerah memiliki satu panduan (led star) dalam melaksanakan pembangunan nasional dan memudahkan melakukan pengawasan oleh rakyat (pelaksanaan kedaulatan rakyat) guna tercapainya tujuan Indonesia merdeka.
Pelaksana kedaulatan rakyat oleh satu lembaga tertinggi MPR berubah menjadi oleh banyak lembaga negara dan lembaga negara bantu lainnya menimbulkan kesulitan tersendiri bagi rakyat melaksanakan kewajibannya yaitu mengawasi jalannya penyelenggara pemerintahan.
Pengawasan yang efektif adalah proses memastikan bahwa pelaksanaan pembangun-an berjalan sesuai dengan rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya GBHN rakyat akan lebih mudah dan terarah dalam melakukan pengawasan tanpa menimbulkan kegaduhan. Tidak dilibatkannya rakyat secara institusional dalam perencanaan pem-bangunan nasional, pembuatan kebijakan, dan perumusan peraturan perundang-undangan sejak awal akan membuat rakyat merasa asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegera, akibatnya mereka mudah dihasut untuk melakukan penolakan terhadap kebijakan dan pembangunan nasional.
Apabila dalam suatu sistem pemerintahan didapati satu cabang kekuasaan menjadi terlalu dominan, mengabaikan atau menekan cabang kekuasaan lainnya, maka ini mengindikasikan bahwa prinsip checks and balances tidak efektif. Ketidak efektifan ini dapat termanifestasi dalam bentuk penyalahgunaan kekuasaan, inefisiensi dalam pembuatan kebijakan, atau bahkan munculnya otoritariani-sme. Bentuk-bentuk penyalahgunaan kekuasaan itu seperti : korupsi, nepotisme, atau tindakan sewenang-wenang lainnya. Sedangkan inefisiensi terjadi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, proses pembuatan dan persetujuan kebijakan serta peraturan perundang-undangan menjadi lambat, menguntungkan pihak-pihak tertentu, tidak efektif, atau bahkan terhenti karena konflik antar cabang kekuasaan.
Efektivitas pengawasan penyelenggara pemerintahan dalam segala aspeknya guna mencegah penyimpangan, penyalahguna-an wewenang, dan korupsi sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, transparansi dan akuntabilitas dari lembaga pengawas itu sendiri. Lembaga pengawas yang memiliki tingkat transparansi dan akuntabilitas rendah tidak akan dipercaya oleh publik dan tidak akan memiliki kemampuan yang lebih
baik dalam mendeteksi dan mencegah praktik penyalahgunaan kekuasaan dan perilaku tercela lainnya. Ketika proses pengawasan tertutup dan tidak dapat diakses oleh publik akan membuat masyarakat lebih yakin, bahwa lembaga tersebut beroperasi tidak jujur dan koruptif. Kedua, ketersediaan sumber daya yang memadai, baik dalam hal anggaran maupun sumber daya manusia, sangat menentukan sejauh mana pengawasan dapat dilakukan secara optimal.
Dalam Praktik sistem penyelenggara pemerintahan Indonesia, kader-kader partai yang sama atau yang berkoalisi dengan partai penguasa dapat menduduki jabatan-jabatan strategis dalam lembaga negara maupun lembaga negara bantu. Hal ini dimungkinkan karena diterapkannya politik transaksional untuk memenangkan kontestasi pemilihan umum. Dalam kondisi demikian maka sistem checks and balances tidak akan efektif. Kader partai yang berasal dari partai yang sama atau koalisinya tetapi mengendalikan atau berkuasa di lembaga negara yang berbeda sangat potensil melakukan nepotisme. Terlebih-lebih masyarakat Indonesia masih memiliki budaya kondusif (ewuh pakewuh) terhadap perilaku korup.
Baca juga: Willem Frans Ansanay, Nakhoda Baru Bara JP: Menjaga Jejak Jokowi, Mengawal Visi Prabowo-Gibran
Perubahan yang tidak kalah pentingnya adalah peniadaan utusan golongan dan daerah dari keanggotaan MPR RI. Utusan golongan dan utusan daerah-daerah digantikan menjadi Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Perubahan tersebut se-tidak-tidaknya memiliki empat dampak negatif yaitu :
1) berkurangnya representasi berbagai kepentingan golongan dan daerah dalam pengambilan keputusan di tingkat nasional, serta potensi melemahnya semangat kebangsaan dan persatuan.
2) hilangnya utusan daerah dan golongan juga dapat mengurangi legitimasi MPR di mata masyarakat, karena tidak lagi sepenuhnya mencerminkan keberagaman bangsa Indonesia.
3) lembaga MPR tidak ubahnya lembaga politik, karena anggotanya didominasi DPR (utusan partai).
4) walaupun telah ada Putusan Mahkamah Konstitusi12) yang melarang pengurus partai politik mencalonkan diri sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah namun partai dapat saja menyodorkan anggota partainya untuk men-calonkan diri menjadi anggota DPD.
Jumlah anggota MPR pada setiap pemilu pasca reformasi didominasi oleh utusan partai politik (DPR). Anggota MPR tahun 2004 berjumlah 678 orang, terdiri dari DPR 550 orang (81 %) dan DPD 128 orang (19 %). Walaupun jumlah absolut anggota MPR berubah, namun persentasi 81 % anggota DPR dan 19 % anggota DPD bertahan hingga pemilu tahun 2019. Jumlah anggota MPR pada tahun 2019.
Baca juga: Forkonas PP DOB Desak Pemerintah Buka Moratorium, PPPT Resmi Masuk Struktur Nasional
12) Keputusan Mahkamah Konstitusi RI No. 30/PUU-XVI/2018.
711 orang, terdiri dari anggota DPR 575 orang (81 %) dan anggota DPD 136 orang (19 %).13) Persentase anggota DPR di MPR mengalami penurunan 2 % menjadi 79% dan anggota DPD naik menjadi 21 % dibandingkan tahun 2019.
Angka-angka tersebut di atas mem-buktikan, bahwa MPR tidak saja kehilangan kewenangan dan statusnya sebagai lembaga tertinggi negara, tetapi kini sepenuhnya berada dibawah kendali partai politik. Berdasarkan kenyataan tersebut di atas layak diragukan efektifitas pengawasan antar lembaga negara berdasarkan prinsip checks and balances.
C. Kesimpulan
Bahwa dalam filsafat Pancasila, negara adalah organisasi dari sekelompok manusia tertentu (sila 2 dan 3) yang berusaha untuk mencapai kehidupan bersama yang berkesejahteraan dan berkeadilan (sila 5) dengan cara musyawarah/mufakat (sila 4), namun sekelompok manusia yang berorganisasi itu menyadari, bahwa berhasil atau tidak usaha tersebut tergantung dari berkat Tuhan Yang Maha Esa (sila 1).
Demokrasi dan kedaulatan rakyat adalah dua konsep yang keterkaitannya erat. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang dirancang untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan dan keadilan, sedangkan kedaulatan rakyat adalah fundamentum sistem demokrasi.
13)https://mpr.go.id/berita/711-anggota-mpr-ri-periode-2019-2024-dibekali-materi-4-pilar
Indonesia tidak menganut demokrasi liberal model barat, tetapi demokrasi Pancasila.
Bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat (kewajiban mengawasi) baik secara organisasi maupun kelompok lebih terkoordinasi pada masa sebelum perubahan UUD NRI 1945. Pengawasan dilakukan melalui satu pintu yaitu MPR.
Rakyat menemui kesulitan mengawasi penyelenggara pemerintahan pasca perubahan UUD NRI 1945 yaitu menurut UUD, karena pelaksana kedaulatan rakyat tersebar di banyak lembaga negara dan lembaga negara bantu.
Prinsip checks and balances lebih efektif diterapkan sebelum perubahan dibandingkan setelah perubahan UUD 1945, karena kader-kader partai yang sama atau koalisi partai penguasa diberi kesempatan yang seluas-luasnya mengendalikan lembaga negara maupun lembaga negara bantu.
———————–
Daftar bacaan :
Azizah Rima Gitacahyani1, Farrel Arrigo., Regita Kisnanda Putri., Kuswan Hadji., Keefiktifan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Masa Orde Baru dan Masa Reformasi, Lontar Merah Vol. 7 No 1 (2024)
Bunyamin dan Huda, “Politik Hukum Pelembagaan Komisi-Komisi Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” 94.
Kartohadiprodjo Soediman., Pantja-Sila dan/dalam Undang-Undang Dasar 1945. Binatjipta, 1968.
Kelik Iswandi dan Nanik Prasetyoningsih, “Kedudukan State Auxiliary Organs dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia,” Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan 1, no. 2 (2020)
Laurensius Arliman, “Kedudukan Lembaga Negara Indonesia Untuk Mencapai Negara Hukum,” Jurnal Kertha Semaya 8, no. 7 (2020): 1039.
Nurul Huda, Hukum Lembaga Negara (Bandung: Refika Aditama, 2020)
Pusat Pengkajian MPR RI., Reformulasi dan Upaya Memperkokoh Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, 2014.
Peraturan dan Perundang-undangan :
Keputusan Mahkamah Konstitusi RI No. 30/PUU-XVI/2018 tentang Konflik Kepentingan Fungsionaris Partai Yang Menjadi Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
Undang-Undang No. 25 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Website :
https://mpr.go.id/berita/711-anggota-mpr-ri-periode-2019-2024-dibekali-materi-4-pilar



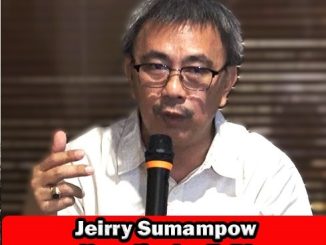
Be the first to comment